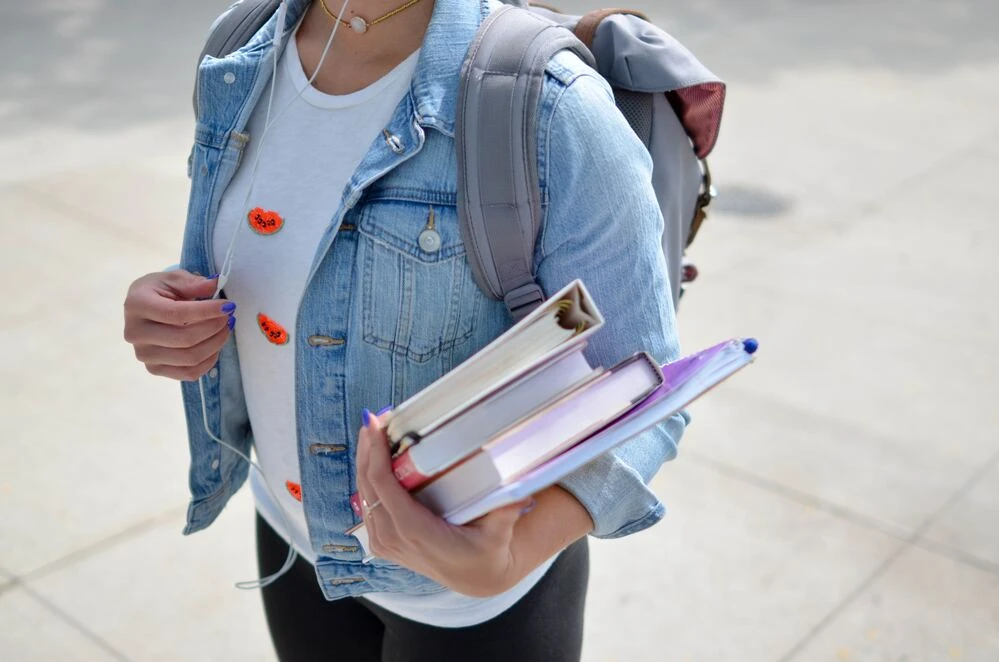Mengenal Apa itu Reverse Culture Shock Saat Tinggal di Luar Negeri
Pasti selalu ada momen yang membuat kita lebih celik terhadap titik balik kehidupan, dan hal tersebut akan terus membekas di benak kita. Salah satunya seperti yang terjadi pada saya: di tanggal 29 Juni 2016, saat di mana saya sedang mengalami situasi kritis. Saya menetap di Amterdam untuk sekolah, hal itu terjadi di jam 3 pagi. Hanya dalam satu jam, saya seharusnya sudah terbang pulang menuju Kanada. Sebelum melakukan perjalanan, wajah saya memerah – menghadap ke tempat duduk toilet, saat itu badan saya bergetar secara intense, memuntahkan segala hal yang ada di dalam perut saya. Beruntung, terdapat salah satu pelajar internasional yang membantu saya untuk menghubungi ambulans.
Itu merupakan momen panic attack yang saya alami pertama. Nyatanya, kejadian itu juga bukan terakhir halinya. Selama setengah tahun lalu, saya meninggalkan perkuliahan saya. Kampus saya dikenal sebagai sekolah yang dipenuhi oleh pelajar sukses dan penuh ambisi (menjadi salah satu perkuliahan terbaik di seluruh dunia, so you can imagine it). Saya butuh istirahat dari tekanan yang selama ini menerpa saya. Di Amsterdam, saya menemukan kenyamanan yang selama ini saya inginkan. Saya mengambil beberapa kelas sosiologi, dan selama enam bulan tersebut, saya seperti diberikan ‘pencerahan’ akan bagaimana cara saya memandang dunia. Saya menemukan berbagai kesamaan yang membentang budaya (pada akhirnya, kita hanya membutuhkan seseorang yang mau diajak hang out dan menghabiskan bersama di depan TV) serta teman dan keluarga baru dari berbagai wilayah. Saya jatuh cinta dengan kota ini, hidup tampak seperti berjalan secara perlahan, diselimuti dengan keceriaan.
Ketika berada di mobil ambulans, saya hanya ingin segera sampai di rumah sakit dan menyelesaikan ketidaknyamanan ini. Rencana saya adalah untuk kembali ke Kanada dan tinggal di apartment perkuliahan di musim panas, mengerjakan resume untuk sekolah pascasarjana, dan persiapan GRE. Tetapi rencana itu buyar saat saya sedang berusaha keras melawan kegelisahaan dan depresi yang saya alami. Mau tak mau, saya harus kembali ke orang tua saya dalam delapan jam ke depan. Saya mampu merasakan beban rasa sedih yang menetap di atas dada saya, layaknya seperti menindih dada saya. Saya bahkan tak ingat bagaimana caranya untuk bisa merasa bahagia. Kalau saja saya membayangkan kehidupan yang hopeless, saat itu pula rasa panik itu muncul – muntah, dan kemudian berakhir di Emergency Room.
Saya diberikan obat penenang dengan dosis tinggi, saya mengatakan kepada dokter, kalau saya pun tak paham mengapa saya terus menangis tanpa henti. Hidup saya diliputi oleh teman, keluarga, hubungan yang sehat, keuangan yang cukup, serta nilai GPA yang baik di sekolah. Tetapi pikiran saya selalu berlarian ke sana dan ke mari, jatung saya berdegup kencang, lantaran peperangan antara otak dan tubuh saya. Setelah diberikan resep obat penenang dan antidepressant, dokter menjelaskan bahwa gejala ini merupakan bagian dari reverse culture shock, emosi dan psikis kita terkadang diderita oleh situasi tersebut. Dokter menambahkan, diagnosa ini masih tak tercatat resmi secara medis – dan mungkin akan segera tercantum – karena sejatinya, fenomena seperti ini sudah bukan hal baru lagi untuk dialami oleh banyak orang. (Ada buku yang penulis tentang kondisi tersebut, salah satunya yakni The Art Of Coming Home karya Caig Storti). Setidaknya, saya sudah tahu kondisi kesehatan saya secara gamblang.
Sebagai pelajar psikolog, saya melakukan investigasi mendalam dan menemukan sosok Janice Abarbanel, PhD. Ia melakukan riset terkait pengaruh mental dari hidup merantau di luar negeri, dan menyatakan bahwa para perantau muda seringkali takmemiliki banyak bekal secara emosional ketika harus menghadapi transisi budaya. Seperti rasa kangen terhadap keluarga, menginginkan kebebasan, menyadari kalau kamu lebih menyukai budaya di tempat baru, mixed feelings altogeher. Abarbanel menjelaskan dalam tulisannya, semua ini akan terasa melelahkan, karena rasa stres yang dialami tentu akan memengaruhi kemampuan otak kita dalam menyelesaikan masalah, serta menemukan perspektif baru. Itu-lah mengapa gejala reverse culture shock dapat terjadi dalam kurun waktu yang instan, khususnya bagi seseorang seperti saya, yang tadinya menerapkan slow living, lalu secara mendadak diharuskan untuk hidup dipenuhi dengan interaksi sosial.
Saran dari Abarbanel? Berikan para perantau “emotional passport” yang melibatkan kesadaran para pemilik, akses untuk konseling atau terapi, dan laporan keahlian yang dimiliki mereka baik setelah dan sesudah merantau. Sayangnya, sekolah saya tidak menyediakan bantuan tersebut, namun kalau dipikir kembali...saya merasa tak begitu membutuhkannya. Karena kamu tak bisa membenahi suatu hal yang belum terlihat akar masalahnya, itu-lah mengapa perbincangan seputar reverse culture shock sangat dibutuhkan. Harapan saya: Karena sejak lama saya terlalu menutup diri dan tidak terbuka terhadap perasaan saya terhadap hidup merantau, kini saya bertujuan untuk menyalakan ‘lampu’ dalam jiwa saya, dengan memperlihatkan kehidupan yang saya alami terhadap orang-orang yang saya percaya.
Saya tak pernah menyalahkan Amsterdam akan penderitaan ini – karena yang saya butuhkan adalah fase pengenalan terhadap tempat tinggal baru saya, wish I knew it sooner. Membutuhkan enam tahun untuk tetap bertahan dari kondisi ini, obat antidepressant (ya, saya masih mengonsumsinya), serta momen introspeksi diri yang membuat saya kini kembali hidup. Saya mencoba untuk menghabiskan waktu lebih bermakna saat traveling – menjadi bagian terpenting dalam pekerjaan saya – tanpa adanya rasa takut, secara fisik dan emosional, saya sudah siap menggenggam passport, and ready to go.
(Artikel ini disadur dari cosmopolitan.com / Artikel berdasarkan kisah dari Penulis asli: Hannah Chubb / Alih Bahasa: Nadhifa Arundati / Image: Dok. by Element5 Digital on Unsplash)