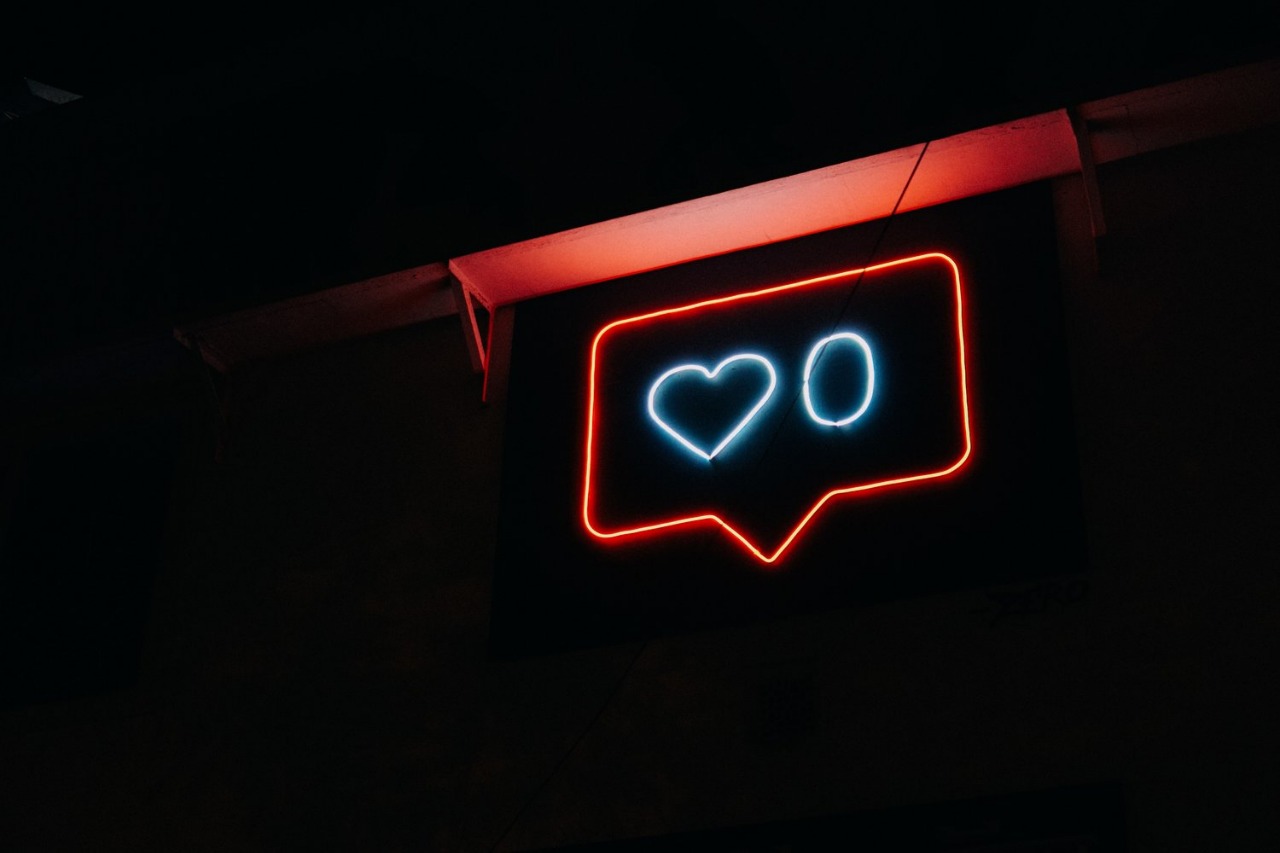Semua Yang Perlu Kamu Tahu Soal Cancel Culture
- Cancel culture lahir sebagai bentuk demokrasi media sosial yang semakin kritis pada isu-isu sosial.
- Seperti pedang bermata dua, cancel culture dapat berfungsi sebagai alat keadilan sosial sekaligus senjata intimidasi massal.
Beberapa tahun terakhir ini, istilah "cancel culture" semakin lazim kita lihat di berbagai media sosial, khususnya di Twitter. Secara sederhana, cancel culture merujuk pada gagasan untuk “membatalkan” seseorang dengan arti memboikot atau menghilangkan pengaruh orang tersebut baik di media sosial maupun nyata. Polanya biasanya seperti ini, seorang public figure melakukan atau mengatakan sesuatu yang dianggap ofensif atau problematik kemudian publik merespons di media sosial dengan efek bola salju yang makin lama makin membesar sampai akhirnya ada yang menyerukan si public figure pantas “di-cancel” yang bisa diartikan ajakan untuk mematikan karier maupun pengaruh si public figure, baik dengan cara memboikot karyanya atau bahkan meminta hukuman dan pertanggungjawaban yang lebih tegas dari industri, kantor, dan institusi lain yang berkaitan dengannya. Berikut adalah beberapa hal yang harus kamu tahu lebih dalam tentang cancel culture itu sendiri.
Dari mana istilah “Cancel” muncul?
Untuk mengetahui lebih dalam soal cancel culture, kita mungkin harus mengetahui asal-muasal dari istilah itu sendiri. Walaupun sering dipakai untuk melawan perbuatan yang dianggap seksis dan rasis, namun ironisnya, Aja Romano dalam artikelnya untuk Vox menjelaskan bahwa konsep “cancelling” ini akarnya justru dari candaan misoginis. Ia menulis, “Mungkin referensi pertama untuk istilah ‘meng-cancel’ seseorang berasal dari film tahun 1991 berjudul New Jack City di mana Wesley Snipes bermain sebagai seorang gangster bernama Nino Brown. Di satu adegan, setelah kekasihnya menangis karena semua kekerasan yang disebabkan olehnya, Nino mencampakkan pacarnya dengan berkata, ‘Cancel that b*tch. I’ll buy another one.’”
Lompat ke 2010, rapper Lil Wayne kemudian memasukkan referensi adegan tersebut ke lagunya yang berjudul “Single” dengan lirik: “Yeah, I’m single / n***a had to cancel that bitch like Nino.” Namun, menurut Aja istilah “cancel” baru banyak dipakai setelah salah satu episode reality show VH1 berjudul Love and Hip-Hop: New York yang tayang Desember 2014 menampilkan adegan salah satu bintangnya Cisco Rosado berteriak pada gadis incarannya “You’re canceled” setelah mereka bertengkar.
'.
Dalam wawancara dengan Vogue, Taylor mengungkapkan pengalaman tersebut, “Saya rasa tidak banyak orang yang bisa memahami bagaimana rasanya ketika jutaan orang mengungkapkan kebencian mereka padamu. Ketika kamu bilang seseorang “di-cancel”, ini bukan serial TV, ini adalah manusia. Kamu mengirim pesan bertubi-tubi ke orang itu untuk tutup mulut, menghilang, atau bahkan bisa diartikan sebagai pesan untuk orang itu bunuh diri.”
Konsekuensi dari cancel culture.
Sebagai fenomena yang lahir di internet, cancel culture pada awalnya lebih sering berakhir sebagai wacana internet saja, tanpa menimbulkan konsekuensi yang nyata pada pihak yang “di-cancel”. Zaman sekarang, blunder sedikit saja bisa bikin seorang selebriti mendapat “kado” tagar #__IsOverParty di Twitter tapi terus bagaimana? Publik umum yang bukan pengguna aktif Twitter mungkin tak peduli dengan isu tersebut dan si seleb tak terpengaruh soal itu. Begitu pun dengan sosok influencer yang blunder, biasanya mereka tinggal posting permintaan maaf, menghapus konten yang bermasalah, absen sejenak dari medsos untuk sementara waktu, lalu kembali seolah tak ada masalah apa-apa.
Tapi, makin ke sini, cancel culture juga punya konsekuensi yang lebih nyata. Contohnya seperti Lea Michele yang kontraknya dengan sebuah brand dibatalkan menyusul tuduhan rasis padanya hingga YouTuber Ferdian Paleka yang membuat “prank” pada kaum transgender dan sempat ditahan polisi setelah konten tersebut heboh “di-call out” di media sosial dan di-blow up oleh media massa. Hal ini mungkin karena belakangan ini media massa pun banyak yang mencari berita dari media sosial hingga isu apapun yang sedang panas di medsos bisa lebih cepat terekspos dan tersebar ke orang yang bahkan tidak terlalu sering membuka medsos.
Cancel culture. Yes or no?
Pada akhirnya, cancel culture telah menjadi bagian dari kehidupan bermedia sosial kita dan tampaknya memang belum akan menghilang. Pertanyaan apakah cancel culture perlu dipertahankan atau tidak, semuanya harus melihat kasus per kasus yang ada dan tidak bisa disamaratakan.
Misalnya, call-out dan cancel yang menimpa seseorang yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Si korban mungkin merasa malu bila harus ke pihak berwajib dan akhirnya memilih bercerita ke media sosial baik melalui akunnya sendiri (entah itu anonim atau tidak) atau melalui akun temannya yang mengangkat masalah itu (call-out) ke ranah publik dan meminta pertanggungjawaban si tertuduh. Ketika publik mulai terlibat, di situlah cancel culture muncul. Sebetulnya yang kita tunggu adalah apakah si tertuduh mengakui dan berani bertanggung jawab atas hal itu atau tidak, namun sering kali karena terlalu emosi, banyak orang yang justru membabi-buta menyerang si tertuduh tanpa mendengar cerita dari sisinya dan tak ada bedanya seperti tindakan main hakim sendiri.
Cancel culture dan call-out culture bisa jadi alat perubahan positif bila niatnya dan tujuannya memang beralasan. Seperti misalnya majalah Vogue US yang baru-baru ini di-call out karena dianggap kurang merepresentasikan para talenta kulit hitam (editor, fotografer, model) sehingga sebagai balasannya orang-orang membuat tantangan #VogueChallenge di mana para fotografer dan model kulit hitam membuat kover Vogue versi mereka sendiri.
Namun bagaimana dengan orang yang “di-cancel” karena kesalahan masa lalu? Seperti Rich Brian misalnya yang sempat diangkat tweet masa lalunya ketika ia masih aktif di Twitter dan menggunakan kata-kata slang bahasa Inggris yang problematik atau ketika ia masih memakai nama Rich Chigga yang dianggap ofensif. Well, untuk kasus nama, Brian sendiri telah mengakui kekeliruannya dan itu juga sebabnya ia mengganti nama panggungnya menjadi Rich Brian, karena ketika memakai nama Rich Chigga ia tak menyangka ia akan sesukses sekarang dan hanya bermula dari keisengan. Sementara tweet-tweet lamanya diambil ketika ia masih sangat muda. Dengan bertambahnya umur dan pengalaman, seseorang tentu bisa berubah lebih baik. Karena itu tak adil rasanya bila meng-cancel seseorang karena suatu hal masa lalu ketika mereka mungkin belum paham.
“Call-out” atau menegur orang karena “dosa masa lalu” adalah hal mungkin masih bisa dianggap wajar namun tak serta-merta membuat orang itu pantas di-cancel begitu saja. Kita lihat dulu apakah orang itu berani menjelaskannya apa tidak, terutama kalau ia mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk tak mengulanginya lagi. Kita percaya pada kesempatan kedua dan personal growth seseorang. Kalau sudah diingatkan namun orang itu masih “batu” atau malah mengulangi perbuatannya, baru orang itu mungkin memang pantas di-cancel.
Di penghujung hari, cancel culture juga menjadi hal yang bersifat pribadi dan kembali ke diri kita masing-masing. Kamu lah yang menentukan apakah seseorang pantas di-cancel atau tidak, setidaknya untuk standar moral dirimu sendiri dan nilai-nilai personal yang kamu anut. Tapi rasanya semua orang akan sepakat kalau bijak dalam menggunakan media sosial adalah kunci utama sebelum kita meng-cancel atau di-cancel orang lain. Edukasi, tegur, ingatkan terlebih dahulu sebelum menyerukan cancel ke seseorang. Setuju?
(Alex.K/Image: Prateek Katyal on Unsplash)